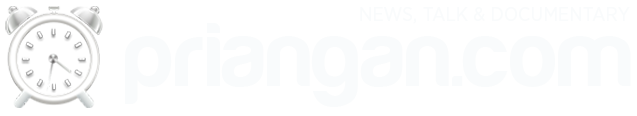SUKABUMI | Priangan.com – Pada abad ke-19, bahasa Sunda mulai mendapat perhatian serius dari bangsa Belanda. Kesadaran itu tumbuh seiring diberlakukannya Regeringsreglement van 1818, sebuah peraturan yang mengatur tata kelola pemerintahan kolonial di Hindia Belanda. Para pejabat dan pengusaha Belanda, terutama yang berkepentingan di wilayah Priangan, menyadari bahwa penguasaan bahasa lokal bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.
Apalagi ketika perkebunan-perkebunan Belanda, atau yang mereka sebut ‘onderneming’, mulai mendominasi perekonomian di daerah tersebut. Interaksi langsung dengan para buruh lokal menuntut kecakapan berbahasa dan dari situlah lahir gagasan untuk membuat panduan belajar bahasa Sunda secara sistematis.
Salah satu tokoh awal yang menunjukkan ketertarikan kuat terhadap bahasa Sunda adalah Andries de Wilde. Ia bukan sekadar tuan tanah di Sukabumi, tetapi juga seorang pengamat sosial yang memahami betul pentingnya komunikasi yang setara dengan masyarakat lokal. Pengalamannya sebagai pengawas budidaya kopi sejak 1808 membuatnya akrab dengan kehidupan masyarakat Priangan, termasuk bahasa dan aksara yang mereka gunakan.
Ia menyusun sebuah buku panduan belajar bahasa Sunda berjudul Nederduitsch-Maleisch en Soendasch Woordenboek: benevens Twee Stukken tot Oefening in Het Soendasch yang diterbitkan pada 1841. Karya ini mendapat pengantar dari linguis terkemuka Taco Roorda, yang memuji ketekunan Wilde dalam merumuskan senarai kosakata serta kecermatannya mempelajari adat-istiadat lokal.
Bahkan, menurut catatan Hawe Setiawan dalam tulisan Atep Kurnia, Wilde sempat mengumpulkan anak-anak muda dan mengajarkan mereka baca-tulis dalam bahasa Sunda dan Melayu menggunakan aksara Latin maupun aksara Jawa.
Setelah kembali ke Eropa, Wilde terus melanjutkan minatnya terhadap bahasa Sunda. Atas dorongan J.F.C. Gericke, ia akhirnya menerbitkan daftar kosakata yang telah dikumpulkannya. Karyanya diakui sebagai kontribusi awal yang penting dalam pengembangan kajian kebahasaan mengenai Sunda dan Melayu oleh kalangan Eropa.
Minat terhadap bahasa Sunda tidak berhenti di situ. Pada pertengahan abad ke-19, muncul Jonathan Rigg, seorang tuan tanah di wilayah selatan Buitenzorg atau yang kini menjadi Bogor. Ia terpacu menyusun kamus Sunda-Inggris setelah pemerintah kolonial mengadakan sayembara untuk mencari panduan belajar bahasa Sunda yang lebih unggul dibanding karya Wilde.
Rigg mengumpulkan berbagai dokumen linguistik, termasuk Paririmbuan-ketjap, karya penting dari Bupati Cianjur R.A. Kusumaningrat. Ia juga mendapat bantuan dari Raden Nata Wireja, Demang Jasinga yang terkenal karena penguasaannya terhadap bahasa Sunda. Hasil dari upaya tersebut adalah A Dictionary of the Sunda Language of Java, kamus Sunda-Inggris pertama yang terbit pada 1862 dan menjadi rujukan penting bagi pegawai kolonial maupun peneliti Eropa.
Gelombang ketertarikan terhadap bahasa Sunda juga mengalir ke kalangan misionaris. Sejak paruh kedua abad ke-19, para pengabar Injil mulai mempelajari bahasa lokal ini demi keperluan penyebaran agama. Tokoh-tokoh seperti J.R.F. Gonggrijp, A. Geerdink, G.J. Grashuis, W.H. Engelmann, S. Coolsma, dan H.J. Oosting, turut ambil bagian dalam penyusunan kitab suci dan materi keagamaan berbahasa Sunda. Mereka bukan hanya menerjemahkan teks-teks religius, tetapi juga ikut mengembangkan struktur linguistik yang memungkinkan bahasa Sunda ditulis dan diajarkan secara efektif.
Pada awal abad ke-20, muncul lagi nama Petel, seorang administratur perkebunan teh di Cigentur. Ia menyusun buku panduan percakapan berbahasa Sunda dan Belanda berjudul Soendaneesche Samenspraken met Nederlandschen tekst ten dienste van Geëmployeerde in de Thee Cultuur yang diterbitkan tahun 1912.
Buku ini dibuat sebagai panduan praktis bagi para calon pegawai perkebunan teh yang ingin bekerja di kawasan Priangan. Bahkan, kamus ini dijadikan tolok ukur seleksi bagi pelamar kerja Belanda di sektor perkebunan, menunjukkan betapa pentingnya penguasaan bahasa lokal bagi roda ekonomi kolonial.
Berbagai upaya yang dilakukan oleh Wilde, Rigg, para misionaris, hingga Petel bukanlah sekadar bentuk adaptasi kolonial terhadap lingkungan lokal, melainkan bagian dari proses panjang kolonialisasi bahasa dan pengetahuan.
Sayangnya, seiring perubahan zaman dan bergesernya orientasi pendidikan serta teknologi bahasa, karya-karya tersebut mulai terlupakan. Ditulis dalam kombinasi Belanda, Melayu, dan Sunda, kamus-kamus itu kini sulit diakses dan tidak lagi relevan secara praktis.
Minimnya upaya pelestarian, penerbitan ulang, atau digitalisasi turut mempercepat pelupaan. Padahal, jika dibaca ulang dalam konteks sejarah, kamus-kamus ini tak hanya merekam pertemuan dua dunia, antara kolonial dan lokal, tetapi juga mencerminkan bagaimana bahasa pernah menjadi alat diplomasi, kontrol, sekaligus pemahaman lintas budaya di tanah Priangan.
Namun, di sisi lain, karya-karya mereka juga menjadi jendela sejarah yang memperlihatkan bagaimana bahasa Sunda pernah menjadi pusat perhatian dalam interaksi antara dunia Barat dan masyarakat lokal di Jawa Barat. Melalui bahasa, batas antara kekuasaan dan pemahaman menjadi semakin kabur dan di situlah letak kompleksitas sejarahnya. (LSA)