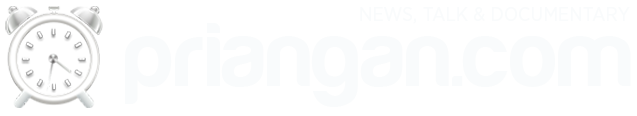JAKARTA | Priangan.com – Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia selama Perang Dunia II, sejarah kelam eksperimen medis tidak hanya terjadi di Manchuria, Tiongkok, tempat Unit 731 dan praktik brutalnya. Peristiwa serupa juga berlangsung di Indonesia, meskipun tidak seterkenal kasus di luar negeri. Salah satu kejadian memilukan terjadi pada tahun 1944 ketika para pekerja paksa atau romusha asal Pekalongan yang ditempatkan di kamp penampungan Jakarta mengalami demam tinggi dan kejang. Gejala ini mengarah pada penyakit tetanus.
Beberapa dari mereka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang saat itu bernama Rumah Sakit Ika Daigaku. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa para pasien sebelumnya telah menerima imunisasi terhadap kolera, tifus, dan disentri. Ketiga penyakit ini umum menyerang penghuni kamp penampungan. Para dokter yang merawat mencurigai imunisasi sebagai penyebab gejala dan segera melaporkannya kepada dokter senior Jepang bernama Kurusawa. Laporan tersebut diteruskan kepada lembaga penanganan romusha agar imunisasi dihentikan.
Sayangnya, peringatan tersebut diabaikan oleh Markas Besar Angkatan Darat ke-16 Jepang yang memimpin pemerintahan di Jawa saat itu. Proses imunisasi tetap dilanjutkan pada tanggal 7 dan 8 Agustus 1944 di kamp romusha yang berada di Klender.
Akibatnya, alih-alih meredakan masalah, jumlah korban justru meningkat. Satu minggu setelah imunisasi, laporan militer mencatat bahwa 107 pekerja dari Pekalongan dan Semarang mengalami gejala serupa. Sebagian besar dari mereka meninggal dunia.
Kematian para romusha ini memicu penyelidikan oleh kempeitai atau kepolisian militer Jepang yang terkenal kejam pada saat itu. Penyelidikan menghasilkan penangkapan sekitar 20 orang yang diduga terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi. Di antara mereka terdapat Ahmad Mochtar, seorang ahli mikrobiologi sekaligus pemimpin Lembaga Eijkman di Jakarta, serta Suleman Siregar, dokter yang bertugas di lapangan. Ahmad Mochtar dijatuhi hukuman mati, sedangkan Suleman divonis tujuh tahun penjara dan meninggal dalam tahanan.
Namun, dasar tuduhan terhadap keduanya sangat lemah. Sejarawan Jepang Aiko Kurasawa, dalam bukunya yang berjudul “Kemerdekaan Bukan Hadiah Jepang” mengungkapkan bahwa Ahmad Mochtar dan Suleman besar kemungkinan dijadikan kambing hitam. Ia menemukan dokumen arsip militer Jepang yang menunjukkan bahwa narasi keterlibatan mereka dibentuk dalam proses interogasi oleh kempeitai. Penyelidikan awal semula mengarah kepada Suleman, tetapi karena pengaruhnya dianggap terlalu kecil, pihak Jepang mengalihkan tuduhan kepada Mochtar.
Ahmad Mochtar bersama stafnya dipaksa mengaku bahwa vaksin yang digunakan mengandung bakteri Clostridium tetani yang menjadi penyebab penyakit tetanus. Kurasawa mencatat adanya kejanggalan dalam laporan-laporan militer Jepang. Versi cerita berubah-ubah, jumlah tersangka menyusut, dan akhirnya hanya menyisakan dua nama sebagai penanggung jawab. Kurasawa menduga hal ini dilakukan untuk menutupi kesalahan produksi vaksin oleh pihak Jepang sendiri.
Namun, fakta yang kurang disoroti adalah vaksin tersebut diproduksi oleh Pasteur Institute di Bandung yang kini dikenal sebagai Bio Farma. Pada masa pendudukan, lembaga ini berada di bawah kendali militer Jepang dan diberi nama Rikugun Boeki Kenkyujo. Peneliti dan dokter Belanda yang sebelumnya bekerja di sana disingkirkan. Direktur lembaga tersebut, Kikuo Kurauchi, merupakan ilmuwan yang didatangkan dari Unit 731 di Manchuria dan dikenal memiliki ambisi besar dalam riset vaksin.
Kurasawa memperkirakan bahwa Kurauchi mencoba berbagai cara untuk memproduksi vaksin tetanus. Ia bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa vaksin eksperimental itu diuji coba langsung kepada manusia. Para romusha kemungkinan besar dijadikan subjek uji coba tanpa persetujuan. Jika eksperimen gagal dan mengakibatkan korban jiwa, maka dokter-dokter Indonesia yang dituduh sebagai pihak yang bersalah.
Vaksin tetanus sendiri ditemukan pada tahun 1924 dan mulai digunakan secara luas selama Perang Dunia II, terutama di kalangan militer. Negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Inggris telah memproduksi vaksin ini secara massal. Jepang yang tertinggal dalam pengembangan vaksin berusaha mengejar ketertinggalan tersebut dengan memproduksi vaksin di wilayah jajahan, termasuk di Indonesia.
Tragedi ini menunjukkan bahwa kekejaman perang tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga dalam praktik ilmiah yang mengorbankan nyawa manusia. Kisah Ahmad Mochtar dan Suleman Siregar menjadi pengingat bahwa ilmu pengetahuan tanpa etika bisa berubah menjadi alat kekuasaan yang kejam. Hingga kini, sejarah mereka layak dikenang sebagai pelajaran tentang kemanusiaan, keberanian, dan pentingnya tanggung jawab dalam dunia medis. (LSA)