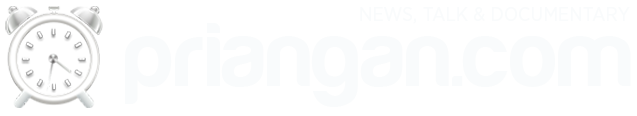JAKARTA | Priangan.com – Pernah dilarang oleh Presiden Soekarno selama hampir empat dekade, lalu diizinkan kembali oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2000, agama Baha’i menyimpan sejarah panjang yang nyaris terlupakan di Indonesia. Meskipun pengikutnya telah hadir di Nusantara sejak akhir abad ke-19, keberadaan mereka sempat tenggelam dalam tekanan kebijakan politik dan sosial.
Baru dalam dua dekade terakhir, komunitas ini kembali menampakkan diri secara terbuka dan berusaha mendapatkan pengakuan yang layak sebagai bagian dari keragaman keyakinan di tanah air.
Namun, kisah Baha’i tak sekadar soal pelarangan dan pembebasan di Indonesia. Agama ini berakar dari Persia abad ke-19, dibawa oleh seorang bangsawan bernama Mirza Husayn Ali Nuri yang kemudian dikenal sebagai Baha’ullah, yang artinya “Kemuliaan Tuhan”.
Di pengasingannya di Baghdad pada tahun 1863, Baha’ullah menyatakan dirinya sebagai utusan Tuhan yang membawa pesan universal tentang kesatuan umat manusia, perdamaian dunia, dan keadilan sosial. Ajarannya melampaui batas agama-agama besar yang sudah mapan dan dengan cepat menyebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke Hindia Belanda melalui jalur pelayaran misionaris Asia Selatan.
Sebelum mendirikan agama Baha’i, Baha’ullah terlebih dahulu menjadi pengikut Sayyid Ali Muhammad, tokoh reformis spiritual yang dikenal sebagai Sang Bab.
Sang Bab dianggap membuka jalan bagi kemunculan nabi baru. Ajarannya ditolak oleh penguasa Persia, dan pada tahun 1850, ia dieksekusi mati bersama sejumlah pengikutnya.
Baha’ullah sendiri sempat dipenjara dalam kondisi yang sangat berat, kaki dipasung, leher dirantai dengan besi seberat 50 kilogram, dan hidup dalam ruang gelap selama berbulan-bulan. Dalam keterasingan itulah ia mengaku menerima wahyu dan penampakan roh teragung.
Setelah dibebaskan, ia diasingkan ke Baghdad bersama keluarganya. Di sana, ajaran Sang Bab kembali ia hidupkan. Pengikutnya semakin bertambah, membuat penguasa Persia cemas dan memintanya diusir.
Sebelum berpindah ke Konstantinopel, pada bulan April 1863, Baha’ullah mengadakan pertemuan dengan para sahabat di sebuah tenda di tepi Sungai Tigris. Di sanalah ia pertama kali memproklamirkan dirinya sebagai utusan Tuhan bagi zaman ini.
Pengasingan pun terus berlanjut, dari Konstantinopel ke Adrianopel, hingga akhirnya ke kota pelabuhan Akka yang kini berada di wilayah Israel. Di kota yang dulu dikenal sebagai tempat pembuangan kriminal oleh Kesultanan Turki Usmani, Baha’ullah menjalani sisa hidupnya selama empat dekade hingga wafat pada 12 Mei 1892.
Ajaran Baha’ullah dilanjutkan oleh putranya, Abdul Baha, yang pada awal abad ke-20 melakukan perjalanan ke berbagai negara untuk menyampaikan misi perdamaian.
Sementara itu, penyebaran agama Baha’i di Asia Tenggara dilakukan oleh Jamal Effendi dari Persia dan rekannya dari Turki, Mustafa Rum. Mereka melakukan perjalanan ke India, Sri Lanka, Burma, hingga ke Malaka.
Pada 1885, mereka berlayar menuju Batavia dan menetap sementara di Kampung Arab Pekojan, Jakarta. Dengan izin pemerintah kolonial Hindia Belanda, mereka melanjutkan perjalanan ke Surabaya, Bali, Lombok, dan Sulawesi.
Dalam perjalanan mereka ke Pare-Pare, mereka diterima oleh Raja Fatta Arongmatua dan putrinya, Fatta Sima Tana. Dua pemuda Bugis, Nair dan Bashir, dipilih untuk ikut bersama mereka dan akhirnya dibawa ke kota Akka untuk mengabdi di rumah Bahji, kediaman Baha’ullah. Sebagaimana dilansir dari DetikX, perjalanan ini mencatat jejak awal masuknya ajaran Baha’i ke wilayah kepulauan Indonesia.
Pada dekade 1950-an, komunitas Baha’i mulai tumbuh kembali di Indonesia, terutama melalui para pendatang dari Persia yang berprofesi di bidang kesehatan dan bersedia ditugaskan di daerah terpencil.
Namun, pada masa pemerintahan Soekarno, tepatnya melalui Keputusan Presiden Nomor 264 Tahun 1962, keberadaan Baha’i kembali ditekan.
Keputusan tersebut tidak hanya melarang Baha’i, tetapi juga membubarkan organisasi-organisasi seperti Freemasonry, Rosikrusian, dan Rotary Club. Pemerintah saat itu memandang organisasi-organisasi tersebut sebagai gerakan transnasional yang dianggap membawa pengaruh ideologis asing serta dinilai dapat mengganggu stabilitas nasional dan ideologi negara. Meskipun tidak secara eksplisit menyasar aspek keagamaannya, Baha’i termasuk dalam kelompok yang terkena dampak kebijakan tersebut dan menghadapi tekanan sosial hingga bertahun-tahun setelahnya.
Sejak itu, umat Baha’i di Indonesia menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan kesulitan mengakses hak-hak sipil.
Larangan tersebut baru dicabut pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melalui Keppres Nomor 69 Tahun 2000. Sejak itulah, komunitas Baha’i di Indonesia mulai tampil lebih terbuka.
Hingga pada tahun 2014, Kementerian Agama melakukan kajian khusus terhadap keberadaan mereka, setelah menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri mengenai status agama ini. Penelitian tersebut mencakup aspek sejarah, ajaran, penyebaran, serta hak-hak sipil umatnya di berbagai daerah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas Baha’i tersebar di Jakarta, Bandung, Bekasi, Pati, Banyuwangi, Malang, Medan, Surabaya, Denpasar, Paloppo, Pekanbaru, hingga Kepulauan Mentawai. Jumlah penganutnya di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 5.000 orang. Mereka memiliki kitab suci Al Aqdas dan sejumlah tulisan suci serta doa yang dikarang oleh Baha’ullah. Praktik keagamaannya meliputi sembahyang wajib tiga kali sehari dan puasa selama 19 hari.
Di tingkat global, menurut data dari The World Almanac and Book of Facts 2004, jumlah penganut Baha’i berkisar antara lima hingga enam juta jiwa. Sebagian besar tinggal di Asia (sekitar 3,6 juta), diikuti Afrika (1,8 juta), dan Amerika Latin (900 ribu). India merupakan negara dengan jumlah penganut terbanyak, sekitar 2,2 juta orang, disusul Iran dan Amerika Serikat.
Antropolog Universitas Indonesia, Amanah Nurish, dalam wawancaranya dengan DetikX, menjelaskan bahwa Baha’i adalah agama monoteis yang mempercayai semua agama bersumber dari Tuhan yang sama. Umatnya menerima agama-agama sebelumnya seperti Hindu, Buddha, Zoroaster, Yahudi, Kristen, dan Islam sebagai bagian dari satu rangkaian wahyu ilahi.
Mereka juga meyakini bahwa ajaran agama bersifat progresif dan akan terus mengalami evolusi sesuai perkembangan zaman. Oleh karena itu, Baha’i tidak memandang dirinya sebagai agama terakhir.
Namun, meskipun dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E dan Pasal 29, umat Baha’i di Indonesia masih kerap mengalami diskriminasi dalam pelayanan publik. Banyak yang kesulitan dalam urusan pencatatan sipil, pendidikan, dan pernikahan karena status agama mereka tidak tercantum dalam daftar agama resmi.
Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama, Nifasri, menyatakan kepada DetikX bahwa meskipun belum ada regulasi formal untuk memfasilitasi agama ini, keberadaan mereka tetap harus dihormati dan dilindungi sebagai bagian dari warga negara.
Ucapan selamat Hari Raya Nawruz atau tahun baru dalam kalender Baha’i oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 2021 sempat menimbulkan polemik.
Beberapa pihak menganggapnya sebagai bentuk pengakuan resmi. Namun menurut Kemenag, pernyataan tersebut murni sebagai bentuk penghormatan atas kebebasan beragama dan keberagaman spiritual masyarakat Indonesia. Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid pun meminta, agar polemik ini dihentikan karena telah berkembang ke arah yang tidak proporsional dan justru mengaburkan semangat toleransi.
Dalam lanskap keagamaan Indonesia yang majemuk, kisah agama Baha’i mengingatkan bahwa perjalanan iman tak pernah lepas dari dinamika sejarah, kekuasaan, dan perjuangan akan pengakuan. Meski belum diakui secara formal, agama ini tetap menjadi bagian dari wajah keberagaman keyakinan di negeri ini, sebuah realitas yang tak bisa disangkal, dan semestinya dihormati bersama. (LSA)