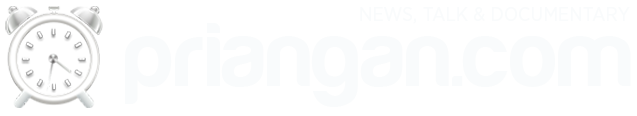JAKARTA | Priangan.com – Berabad-abad lamanya, pesantren telah menjadi denyut nadi kehidupan keislaman di Indonesia. Lembaga pendidikan ini bukan sekadar tempat belajar agama, melainkan juga ruang lahirnya nilai-nilai moral, sosial, dan kebangsaan. Dari kompleks sederhana yang dihuni oleh para santri dan dipimpin oleh seorang kiai, pesantren menjelma menjadi institusi yang membentuk watak dan arah kehidupan umat. Perjalanan panjang bangsa Indonesia pun tidak dapat dilepaskan dari kiprah para santri, baik dalam perjuangan kemerdekaan maupun dalam pembangunan moral masyarakat hingga hari ini.
Peringatan Hari Santri Nasional bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk penghormatan terhadap semangat keikhlasan dan perjuangan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Santri bukan hanya simbol kesalehan, tetapi juga lambang kecintaan terhadap ilmu, tanah air, dan kemanusiaan.
Menariknya, istilah “santri” dan “pesantren” yang begitu akrab di telinga umat Islam Indonesia ternyata bukan berasal dari bahasa Arab. Kata tersebut justru memiliki akar sejarah yang lebih tua, menyentuh masa ketika kebudayaan Hindu-Jawa masih mendominasi pulau Jawa.
Dilansir dari JIB, seorang sejarawan Belanda, C.C. Berg dari Universiteit Leiden, berpendapat bahwa istilah santri diyakini berasal dari bahasa Sanskerta shastri, yang berarti “orang yang mengetahui kitab suci.” Dalam pandangan Berg, kehidupan pesantren di masa Islam merupakan kelanjutan dari tradisi pendidikan mandala atau biara Hindu-Jawa pada masa lampau. Hanya saja, nilai-nilai dan orientasinya kemudian bergeser seiring masuknya Islam ke Nusantara.
Dengan kata lain, pesantren merupakan hasil akulturasi budaya yang berhasil diislamkan, sehingga lembaga ini kemudian sepenuhnya identik dengan tradisi keilmuan Islam.
Istilah pesantren sendiri terbentuk dari kata dasar santri dengan imbuhan pe- dan akhiran -an, yang dalam tata bahasa Jawa menunjukkan tempat. Maka, pesantren berarti “tempat para santri”. Dalam Brill Encyclopaedia of Islam, pesantren dijelaskan sebagai lembaga pendidikan khas Indonesia, di mana para santri mempelajari ilmu-ilmu keislaman klasik dan menjalani kehidupan komunal yang berdisiplin tinggi.
Di tempat lain, istilah “pondok” juga digunakan sebagai padanan, berasal dari kata Arab funduk yang berarti “penginapan”. Perpaduan istilah ini melahirkan sebutan “pondok pesantren”, yang menegaskan fungsi ganda lembaga ini sebagai tempat tinggal sekaligus pusat pendidikan Islam.
Namun, bagaimana mungkin istilah yang berakar dari kebudayaan non-Islam justru menjadi simbol keislaman di Nusantara? Pertanyaan ini membawa kita pada konsep Islamisasi yang dikemukakan oleh S.M.N. Al-Attas. Menurutnya, Islamisasi bukan hanya proses penyebaran agama, melainkan juga penyucian dan penyesuaian makna terhadap istilah-istilah yang telah ada dalam kebudayaan lokal.
Di kepulauan Melayu-Indonesia, banyak istilah yang berasal dari bahasa Sanskerta mengalami perubahan makna setelah bersentuhan dengan Islam. Misalnya, kata puasa yang semula dari “upawasa”, ritual Hindu untuk menahan diri demi penyucian batin, kemudian diislamkan menjadi ibadah shaum dengan makna spiritual yang baru, berlandaskan wahyu. Demikian pula dengan istilah santri, yang mengalami “konversi makna” dari pelajar kitab Hindu menjadi pelajar kitab suci Islam.
Selain penjelasan etimologis dari tradisi Sanskerta, beberapa pandangan lokal juga mencoba menafsirkan makna santri dari perspektif Islam. Dalam buku Sejarah Pergerakan Nasional karya Wahyu Iryana, kata santri dikaitkan dengan lima huruf Arab, yaitu ي ر ت ن س, yang melambangkan karakter seorang santri: meninggalkan maksiat, menutup aurat, berpakaian sopan, menjaga hawa nafsu, dan memiliki keyakinan kuat terhadap cita-cita. Tafsir ini menunjukkan bahwa makna santri telah sepenuhnya terislamkan dan diisi oleh nilai-nilai moralitas Islam.
Sebagian ahli lain, seperti yang dikutip Farid Setiawan dalam Kebijakan Pendidikan Muhammadiyah: 1911–1942, menyebut bahwa istilah ini juga mungkin berasal dari kata Jawa cantrik, yang berarti murid yang mengikuti seorang guru atau pandita. Dalam tradisi lama, seorang cantrik akan tinggal bersama gurunya untuk belajar ilmu dan laku hidup. Ketika Islam datang, tradisi ini tetap dipertahankan, hanya saja gurunya berubah menjadi kiai dan ilmunya berporos pada Al-Qur’an, hadits, dan ilmu keislaman.
Dalam praktiknya, santri terbagi menjadi dua golongan besar, yaitu santri mukim dan santri kalong. Santri mukim tinggal menetap di pesantren karena berasal dari daerah jauh. Mereka hidup dalam asrama sederhana, menempuh kehidupan yang diatur secara ketat, dan memusatkan seluruh waktunya untuk belajar agama.
Sementara itu, santri kalong berasal dari daerah sekitar pesantren dan tidak menetap di sana. Istilah “kalong” diambil dari nama hewan kelelawar besar yang sering bolak-balik dari tempat asalnya, menggambarkan kebiasaan santri yang datang dan pergi setiap hari untuk mengikuti pengajian. Kedua kelompok ini hidup berdampingan dalam sistem pendidikan yang menekankan kemandirian, kedisiplinan, dan kebersahajaan.
Di tengah perubahan zaman yang serba cepat, Hari Santri menjadi pengingat bahwa nilai-nilai pesantren tetap relevan dan dibutuhkan. Dari pesantrenlah lahir generasi yang berilmu dan berakhlak, yang mampu menghadapi tantangan modernitas tanpa kehilangan jati diri. Perjalanan panjang istilah santri dan lembaga pesantren mencerminkan kemampuan Islam untuk berdialog dengan budaya lokal tanpa kehilangan esensinya.
Ini juga menunjukkan bahwa Islam di Nusantara bukan hasil pemaksaan, melainkan proses pembauran nilai yang halus dan beradab. Dari shastri menjadi santri, dari mandala menjadi pesantren, lahirlah satu warisan khas Indonesia, tempatnya ilmu, iman, dan kebudayaan bertemu. Pesantren bukan sekadar saksi sejarah Islam di Nusantara, melainkan juga cerminan dari kearifan bangsa yang mampu menjahit tradisi lama dan ajaran baru menjadi satu kain kebudayaan yang utuh. (LSA)