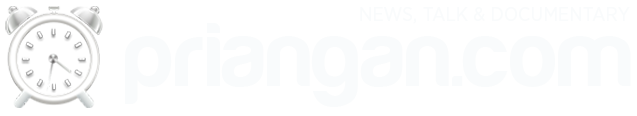TASIKMALAYA | Priangan.com – Angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya yang masih menyentuh 11,10 persen jadi tanda tanya besar tentang arah kebijakan penanggulangan yang selama ini ditempuh pemerintah daerah. Di tengah berbagai forum diskusi dan program intervensi formal, kemiskinan di beberapa wilayah justru menunjukkan wajah yang lebih kompleks dan memprihatinkan.
Di Kecamatan Tamansari, misalnya, masih ditemukan warga yang tinggal tanpa rumah yang layak, bahkan tanpa akses terhadap WC atau sanitasi dasar. Ini bukan sekadar soal penghasilan rendah, melainkan gejala struktural yang lebih dalam.
Akademisi Universitas Cipasung, Rico Ibrahim, menilai bahwa pendekatan yang selama ini dominan terlalu teknokratis dan parsial. Ia menyebutkan bahwa pemerintah kerap terjebak pada pengulangan solusi yang sama: memberikan bantuan materi, memperluas akses pendidikan, atau memperbaiki infrastruktur dasar.
Menurutnya, pendekatan seperti ini memang penting, namun belum menyentuh akar dari persoalan kemiskinan itu sendiri—yakni pola pikir, relasi sosial, serta budaya hidup masyarakat.
“Kemiskinan itu bukan hanya perihal ekonomi, tetapi juga persoalan sosial dan mental. Kita terlalu sering menyederhanakan masalah ini dengan melihatnya hanya dari angka penghasilan atau daya beli. Padahal, masyarakat yang miskin kerap juga miskin harapan, miskin kepercayaan diri, dan miskin solidaritas sosial,” ujar Rico saat ditemui Priangan.com, Kamis (24/7/2025).
Pernyataan Rico ini sekaligus menjadi kritik terhadap pernyataan Wakil Wali Kota Dicky Chandra dalam forum diskusi yang menekankan pentingnya penyelesaian isu-isu seperti status kepemilikan tanah, penghasilan rumah tangga, dan akses pendidikan bagi anak-anak. Menurut Rico, isu-isu tersebut memang valid, tetapi sering kali hanya menyentuh permukaan.
Ia menyayangkan bahwa banyak inisiatif kebijakan yang berhenti pada aspek-aspek yang bisa diukur secara statistik, namun lupa membangun kesadaran dan transformasi nilai di tengah masyarakat.
Rico menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang lebih menyentuh sisi budaya dan struktur sosial masyarakat. Ia mencontohkan bagaimana cara pandang hidup yang statis, penerimaan pasrah terhadap nasib, serta relasi kuasa dalam keluarga—seperti dominasi laki-laki terhadap perempuan—ikut melanggengkan kondisi miskin di berbagai komunitas.
Menurutnya, keluarga yang tidak memberikan ruang setara kepada perempuan akan lebih sulit mengakses peluang kemajuan karena potensi separuh anggota keluarga tidak dimaksimalkan.
Lebih jauh, Rico juga menyoroti lemahnya kepemimpinan lokal dalam merespons kemiskinan. Ia menyebut elite kelurahan dan tokoh masyarakat seringkali bersikap apatis atau bahkan terputus dari realitas sosial warganya sendiri.
“Banyak dari mereka tinggal berdampingan dengan kemiskinan, tetapi tidak merasa berkewajiban untuk ikut menjadi bagian dari penyelesaiannya. Ini persoalan moral dan tanggung jawab sosial yang harus dibangun dari tingkat paling bawah,” tegasnya.
Dalam pandangannya, pembangunan sosial di Tasikmalaya harus diarahkan untuk membentuk budaya kerja keras, kedisiplinan, dan kesadaran kolektif. Ia mencontohkan Jepang sebagai negara yang berhasil membangun kekuatan ekonomi bukan hanya melalui modal dan teknologi, tetapi juga lewat nilai-nilai seperti loyalitas, rasa nasionalisme, dan kohesi sosial yang kuat.
Tasikmalaya, kata dia, bisa memulai dengan hal-hal sederhana: menanamkan nilai bahwa pendidikan anak-anak adalah hal paling utama, membentuk rasa malu untuk hidup dalam kemiskinan, dan menumbuhkan budaya hemat, produktif, dan inovatif.
“Kita butuh menciptakan budaya baru yang mendorong setiap orang untuk keluar dari ketergantungan, malas, dan sikap pasrah. Hidup bukan soal panjangnya cita-cita, tapi bagaimana masyarakat punya visi yang konkret: keluarga mandiri, anak sekolah tinggi, orang tua bekerja keras dengan bangga,” ujar Rico.
Ia berharap pemerintah daerah mulai menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan dengan mempertimbangkan dimensi sosial budaya secara lebih serius. Bukan hanya mengucurkan anggaran, tapi juga membangun kesadaran dan transformasi nilai di tengah masyarakat. Tanpa itu, menurutnya, angka kemiskinan mungkin akan turun secara administratif, tapi kehidupan masyarakat tetap stagnan secara sosial dan mental. (yna)