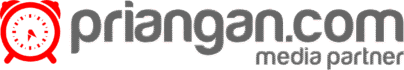BANDUNG | Priangan.com – Nama Raden Otto Iskandardinata sudah lama dikenal sebagai salah satu tokoh besar asal Tanah Sunda. Sosoknya dikenal tegas, berwawasan luas, dan punya kepedulian besar terhadap kemajuan rakyat. Di balik segala perjuangannya, Otto ternyata berangkat dari latar kehidupan yang sederhana namun sarat nilai-nilai pengabdian.
Ia lahir di Desa Bojongsoang, Kabupaten Bandung, pada 31 Maret 1897. Ia berasal dari keluarga menak Sunda yang terpandang. Ayahnya, Raden Haji Rachmat Adam, menjabat sebagai Lurah Bojongsoang, sedangkan ibunya bernama Nyi Raden Siti Hatijah.
Dalam silsilah keluarga, garis keturunannya dipercaya sampai kepada Prabu Siliwangi, raja legendaris dari Tanah Pajajaran. Meski hal itu sulit dibuktikan secara historis, gelar kebangsawanan “raden” yang disandangnya menegaskan posisi keluarganya di tengah masyarakat Priangan pada masa itu.
Sebagai anak bangsawan, Otto kecil mendapat kesempatan pendidikan yang baik. Ia disekolahkan di Hollandsch Inlandsche School (HIS), sekolah dasar bagi kaum pribumi, sambil tetap menapaki pendidikan agama pada sore hari.
Pendidikan ganda seperti ini dulu umum di kalangan menak Sunda yang ingin menguasai pengetahuan modern tanpa meninggalkan akar religius. Ayahnya yang telah menunaikan ibadah haji membuat kedudukannya makin dihormati, dan hal itu turut membentuk pandangan hidup Otto muda tentang kehormatan, tanggung jawab, dan pengabdian.
Sejak kecil, Otto dikenal aktif dan punya jiwa pemimpin. Ia gemar bermain sepak bola, sering turun langsung dalam pertandingan antar sekolah, bahkan pernah menjadi Ketua Persib Bandung bersama Rahim, mertua Bung Hatta. Di luar olahraga, ia juga menyukai kesenian Sunda, seperti menabuh gamelan, menari, dan bermain tonil. Ketertarikannya pada kebudayaan kelak menjadi fondasi perjuangannya dalam memajukan pendidikan dan kebudayaan Sunda melalui Pagoejoeban Pasoendan.
Setelah lulus HIS, Otto melanjutkan pendidikan ke Kweekschool Onderbouw atau Sekolah Guru Bagian Pertama di Bandung. Di sekolah asrama yang terkenal disiplin itu, Otto menonjol karena keberaniannya melawan aturan yang dianggap tidak masuk akal. Meski kerap dihukum, kecerdasan dan semangatnya membuatnya selalu naik kelas dengan prestasi baik. Dari sinilah karakter tegas dan pemberaninya mulai terbentuk, yang kelak menjadikannya sebagau orator tajam di Volksraad.
Setelah menamatkan pendidikan, Otto mengabdikan diri di Banjarnegara sebagai pengajar di HIS. Dunia pendidikan menjadi jalan hidupnya. Ia meyakini bahwa bangsa yang cerdas akan menjadi bangsa yang merdeka.
Di tempat ini pula ia bertemu jodohnya, seorang muridnya sendiri bernama Raden Roro Soekirah. Cinta mereka berlanjut hingga pernikahan pada tahun 1923 di Bandung. Dari keluarga kecil ini kelak lahir banyak anak, tercatat ada dua belas orang semuanya yang dibesarkan dengan kedisiplinan dan semangat nasionalisme.
Kepindahan Otto ke berbagai kota, mulai Bandung, Pekalongan, hingga Batavia, selalu diiringi dengan kiprah di bidang pendidikan dan pergerakan nasional. Di Pekalongan, misalnya, ia tercatat menjadi Wakil Ketua Boedi Oetomo Cabang Pekalongan sekaligus anggota Gemeenteraad (Dewan Kota).
Di lembaga itu, ia berani membongkar kasus penipuan pengusaha Belanda terhadap rakyat di Bendungan Kemuning. Keberaniannya ini membuat pemerintah kolonial marah, bahkan sempat mengancam untuk mengasingkannya. Namun Otto tidak gentar. Tindakannya membela rakyat kecil justru membuat namanya semakin dikenal luas.
Pada tahun 1928, ia pindah ke Batavia dan mengajar di HIS Muhammadiyah. Di kota inilah semangat politiknya semakin menyala. Ia bergabung dengan Pagoejoeban Pasoendan dan tidak lama kemudian didapuk menjadi Ketua Pengurus Besar organisasi itu.
Di bawah kepemimpinannya, Pagoejoeban Pasoendan tumbuh menjadi organisasi besar yang berpengaruh di bidang politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Otto berhasil mengarahkan organisasi ini dari sekadar wadah etnis Sunda menjadi gerakan kebangsaan yang turut memerjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Kiprah politik Otto semakin luas ketika ia menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat pada 15 Juni 1931. Sebagai wakil Pagoejoeban Pasoendan, ia duduk dalam lembaga itu selama tiga periode hingga tahun 1942. Dalam sidang-sidang Volksraad, Otto tampil sebagai pembicara yang tajam dan berani.
Ia lebih sering berbicara dalam bahasa Melayu agar rakyat bisa memahami isi pidatonya, meski hal itu membuat ketua sidang memintanya berbahasa Belanda. Pidato-pidatonya keras, menyentuh kepentingan rakyat dan penuh kritik terhadap kebijakan kolonial. Dari gaya bicaranya yang lantang dan tegas itulah ia dijuluki “Si Jalak Harupat”, simbol keberanian dan ketajaman dalam memperjuangkan kebenaran.
Di Volksraad, Otto tergabung dalam Fraksi Nasional bersama tokoh-tokoh besar seperti Mohammad Hoesni Thamrin dan Soekardjo Wirjopranoto. Ia mendukung Petisi Soetardjo tahun 1936 yang menuntut otonomi bagi Indonesia. Meski petisi itu akhirnya ditolak oleh pemerintah Belanda, sikap Otto mencerminkan komitmennya terhadap perjuangan politik yang rasional dan berorientasi pada kemerdekaan bangsa.
Dalam sidang-sidang lainnya, ia juga menentang pembentukan milisi bumiputra yang dianggap hanya menguntungkan kepentingan Belanda tanpa memberi hak politik bagi rakyat pribumi. Karena pendiriannya yang keras, Oto akhirnya mengundurkan diri dari Volksraad pada tahun 1941.
Di luar dunia politik, Otto punya perhatian besar pada pengembangan pendidikan dan kebudayaan. Di bawah kepemimpinannya, Pagoejoeban Pasoendan mendirikan berbagai lembaga pendidikan di Jawa Barat seperti HIS, MULO, Kweekschool, dan Vakschool untuk perempuan.
Melalui Studiefonds Pasoendan, ia memberikan beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu agar tetap bisa bersekolah. Di sekolah-sekolah ini, para murid diajarkan ilmu pengetahuan umum, nilai-nilai kebangsaan, kesenian Sunda, dan semangat keislaman.
Otto Iskandardinata percaya bahwa pendidikan adalah alat untuk membebaskan bangsa dari kebodohan dan penjajahan. Ia sering berpesan kepada anak-anaknya bahwa seorang pemuda harus mencintai tiga ibu: ibu kandung, ibu dari anak-anaknya, dan ibu pertiwi.
Ibu pertama dan kedua, katanya, harus rela ditinggalkan demi kepentingan ibu yang ketiga, yaitu tanah air. Nilai-nilai inilah yang menjadikan Otto sebagai sosok teladan dalam keluarga dan panutan dalam perjuangan bangsa.
Pada masa pendudukan Jepang, Otto tetap aktif dalam kegiatan sosial dan pendidikan. Ia mendirikan lembaga-lembaga ekonomi seperti koperasi dan bank untuk memperkuat kemandirian rakyat.
Dalam Pagoejoeban Pasoendan, ia membentuk Bale Ekonomi Pasoendan pada tahun 1938 untuk mengkoordinasikan seluruh usaha ekonomi rakyat. Gagasan-gagasannya selalu menekankan pentingnya kemandirian ekonomi dan pendidikan sebagai dasar perjuangan nasional.
Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Otto dipercaya menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan kemudian menjabat Menteri Negara dalam kabinet pertama Republik Indonesia. Namun pengabdiannya tak berlangsung lama. Pada akhir tahun 1945, ia diculik oleh kelompok yang tidak dikenal di wilayah Mauk, Tangerang, dan dinyatakan gugur pada bulan Desember 1945.
Kehilangan Otto Iskandardinata menjadi duka bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Sunda yang menjadikannya simbol keberanian dan pengabdian. Ia tidak hanya dikenal sebagai politisi yang vokal, namun juga seorang pendidik, organisator, dan pejuang kebudayaan. Warisannya masih terasa hingga kini melalui berbagai lembaga pendidikan di bawah naungan Paguyuban Pasundan dan nilai-nilai yang ia tanamkan dalam perjuangan rakyat Priangan.
Nama Otto Iskandardinata kini diabadikan sebagai nama jalan, gedung, sekolah, dan stadion di berbagai kota di Indonesia. Julukan “Si Jalak Harupat” tetap melekat padanya, menjadi simbol keberanian yang tak kenal takut menghadapi penindasan. (wrd)