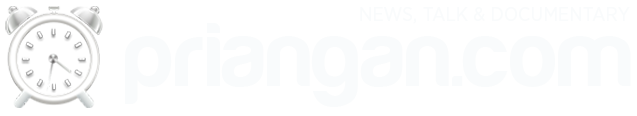PRETORIA | Priangan.com – Di ujung selatan benua Afrika berdiri sebuah negeri yang kaya akan keberagaman. Di sana hidup puluhan kelompok etnis, mulai dari suku Bantu, Khoisan, Xhosa, hingga orang-orang keturunan Belanda dan Eropa yang dikenal sebagai Afrikaner. Bahasa, budaya, dan tradisi bercampur di tanah itu, seolah menjadi mozaik yang indah. Tetapi di balik keberagaman tersebut, pernah ada dinding pemisah yang sangat kejam. Dinding itu bernama apartheid, sebuah sistem yang memisahkan orang hanya karena warna kulitnya. Ketidakadilan yang begitu lama itu akhirnya melahirkan perlawanan, dan dari sana muncullah seorang pemimpin yang kemudian menjadi simbol harapan, Nelson Mandela.
Dilansir dari RT News, sejak awal abad ke-20, kehidupan di Afrika Selatan sangat timpang. Kaum kulit putih, yang jumlahnya jauh lebih sedikit, memegang kendali penuh atas tanah, kekuasaan, dan pendidikan. Sebaliknya, penduduk asli Afrika yang merupakan mayoritas dipaksa hidup di wilayah kecil yang disebut bantustan, dilarang memiliki tanah luas, bahkan tidak memiliki hak pilih. Mereka hanya boleh masuk ke kota besar bila bekerja sebagai buruh atau pelayan. Segala gerak mereka diawasi.
Diskriminasi itu akhirnya dilembagakan pada tahun 1948, ketika Partai Nasional yang dipimpin Afrikaner menang pemilu dan resmi menerapkan sistem apartheid. Aturan ini memisahkan segala hal berdasarkan warna kulit, seperti sekolah, tempat tinggal, hingga akses pekerjaan.
Di tengah kenyataan itulah Nelson Rolihlahla Mandela lahir pada 18 Juli 1918 di desa Mvezo, wilayah Transkei. Nama Rolihlahla dalam bahasa Xhosa berarti “penarik dahan pohon” atau “pembuat onar”. Nama itu ternyata seperti pertanda. Sejak muda, ia memang ditakdirkan untuk mengguncang tatanan yang tidak adil. Nama “Nelson” sendiri baru ia dapatkan ketika seorang guru di sekolah memberinya nama khas Eropa, sesuai kebiasaan masa kolonial.
Mandela tumbuh dengan dua warisan, tradisi sukunya yang menjunjung tinggi musyawarah dan pendidikan Barat yang memberinya jalan mengenal dunia modern. Dari keduanya, ia belajar bahwa kepemimpinan harus dibangun di atas keadilan dan kebijaksanaan.
Masa mudanya diwarnai dengan banyak tantangan. Pada 1939 ia diterima di Universitas Fort Hare, satu-satunya kampus untuk mahasiswa kulit hitam saat itu. Beberapa tahun kemudian ia pindah ke Johannesburg, kota besar yang dipenuhi tambang emas dan jurang ketimpangan sosial. Di sana ia melihat langsung bagaimana orang kulit hitam dipaksa tinggal di perkampungan kumuh, sementara kawasan mewah hanya untuk orang kulit putih. Dalam otobiografinya, Long Walk to Freedom, Mandela menulis bahwa hidup orang Afrika dibatasi oleh hukum dan peraturan rasis yang meredupkan potensinya dan merusak hidupnya.
Perjumpaan dengan kenyataan keras itu membuat Mandela semakin sadar. Pada 1944, ia bergabung dengan African National Congress (ANC), organisasi politik tertua di Afrika Selatan. Bersama kawan-kawannya seperti Oliver Tambo dan Walter Sisulu, ia membentuk Liga Pemuda ANC yang menyerukan kesetaraan bagi semua orang.
Awalnya, ia mengadopsi gagasan perlawanan tanpa kekerasan, terinspirasi oleh Mahatma Gandhi. Pada 1952 ia ikut memimpin Defiance Campaign, aksi protes damai melawan hukum apartheid. Ribuan orang dengan sengaja melanggar aturan, misalnya masuk ke area khusus kulit putih untuk menunjukkan penolakan. Namun pemerintah merespons dengan penangkapan dan kekerasan.
Tragedi besar terjadi pada 1960 di Sharpeville, ketika polisi menembaki massa yang memprotes hukum wajib membawa buku identitas. Sebanyak 69 orang tewas. Sejak saat itu, ANC dilarang, dan Mandela bersama rekan-rekannya menyimpulkan bahwa perjuangan damai tidak lagi cukup. Ia lalu mendirikan uMkhonto weSizwe (MK), yang berarti “Tombak Bangsa”, sebagai sayap militer ANC. Namun perjuangan ini membuatnya ditangkap pada 1962, dan dua tahun kemudian ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dalam Pengadilan Rivonia.
Di ruang pengadilan, Mandela menyampaikan pidato yang kini dikenang dunia: “I have fought against white domination, and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities.” (“Saya telah berjuang melawan dominasi kulit putih, dan saya juga telah berjuang melawan dominasi kulit hitam. Saya menjunjung tinggi cita-cita masyarakat yang demokratis dan bebas, di mana semua orang bisa hidup bersama dalam harmoni dan memiliki kesempatan yang setara.”)
Mandela menjalani 27 tahun di balik jeruji, sebagian besar di Pulau Robben. Ia dipaksa kerja keras di tambang batu, tidur di sel sempit, dan hidup dengan makanan minim. Tetapi penjara tidak mematahkan semangatnya. Justru di balik jeruji ia semakin dikenal sebagai simbol perlawanan. Ia belajar hukum lewat korespondensi, mengajar sesama tahanan, dan menolak tawaran pembebasan bersyarat bila harus meninggalkan perjuangan.
Sementara itu, tekanan terhadap rezim apartheid datang dari dalam dan luar negeri. Dunia internasional memberi sanksi, sementara rakyat Afrika Selatan terus melakukan protes, salah satunya Pemberontakan Soweto 1976 yang menewaskan ratusan siswa. Rezim kian terpojok, hingga pada 11 Februari 1990 Mandela akhirnya dibebaskan. Momen itu disambut gegap gempita oleh rakyatnya dan menjadi titik balik sejarah Afrika Selatan.
Empat tahun setelah kebebasannya, pada 1994, Afrika Selatan menggelar pemilu demokratis pertama dalam sejarah. Untuk pertama kalinya semua warga, tanpa memandang warna kulit, bisa memberikan suara. ANC meraih kemenangan besar, dan Nelson Mandela terpilih sebagai presiden. Masa pemerintahannya difokuskan pada rekonsiliasi nasional, membangun kembali rasa persatuan, dan menghapus warisan diskriminasi. Ia bahkan mengajak mantan lawan politik duduk bersama dalam pemerintahan, sebuah langkah yang menunjukkan kebesaran jiwa.
Mandela hanya menjabat satu periode (1994–1999), lalu dengan rela menyerahkan tongkat kepemimpinan. Sikap itu membuat dunia menaruh hormat karena ia membuktikan bahwa kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk melayani rakyat. Setelah pensiun, ia mendirikan Yayasan Nelson Mandela yang terus bergerak di bidang perdamaian, demokrasi, dan keadilan sosial.
Nelson Mandela wafat pada 5 Desember 2013, tetapi warisannya tetap hidup. PBB bahkan menetapkan Penghargaan Nelson Mandela sebagai bentuk penghormatan bagi mereka yang berkontribusi pada transformasi sosial. Mandela dikenang bukan hanya sebagai pemimpin politik, melainkan sebagai simbol keberanian, pengampunan, dan rekonsiliasi. Ia membuktikan bahwa jalan menuju keadilan tidak pernah bisa ditempuh dengan kebencian, melainkan dengan tekad, kesabaran, dan keberanian untuk memaafkan. (LSA)