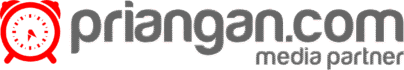JAKARTA | Priangan.com – Pada tahun 1964, Indonesia tengah berada dalam masa-masa penuh tantangan. Berbagai isu, dari ekonomi hingga ketahanan pangan, menjadi perhatian utama pemerintah. Salah satu masalah yang muncul adalah ketergantungan yang berlebihan pada beras sebagai makanan pokok masyarakat.
Kebiasaan ini sudah berlangsung lama dan sulit untuk diubah. Namun, pada suatu hari, Presiden Soekarno mengungkapkan sebuah ide yang cukup unik, yang kemudian dikenal dengan istilah revolusi menu.
Soekarno berpendapat bahwa masyarakat Indonesia perlu menggali potensi pangan lokal yang lebih beragam, seperti jagung, ubi, dan kacang. Ia bahkan memberikan contoh langsung dengan mengungkapkan kebiasaan pribadinya yang rutin mengonsumsi jagung seminggu sekali.
Bagi Soekarno, ini bukan hanya soal variasi makanan, tetapi juga tentang menciptakan ketahanan pangan yang lebih mandiri dan sehat untuk Indonesia. Melalui ajakan ini, ia berharap masyarakat mulai berpikir lebih kreatif tentang konsumsi makanan, yang pada gilirannya bisa membantu memperbaiki kualitas gizi rakyat Indonesia.
Dr. Satrio, Menteri Kesehatan saat itu, pun menyambut baik ide tersebut. Segera setelah itu, berbagai langkah dilakukan untuk memperkenalkan revolusi menu kepada publik. Program ini pun mulai berkembang, menciptakan kesadaran baru akan pentingnya keberagaman makanan untuk kesehatan masyarakat.
Pada masa itu, pemahaman masyarakat Indonesia tentang gizi masih sangat terbatas. Banyak yang tidak menyadari pentingnya pola makan yang seimbang dan keanekaragaman makanan.
Dalam catatan Djaja pada 28 Maret 1964, masih banyak orang yang belum memahami masalah gizi dan seputar makanan. Hal inilah yang mendorong dr. Satrio untuk meluncurkan Operasi Pemberantasan Buta Gizi segera setelah revolusi menu dicanangkan.
Program ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya makanan bergizi, terutama bagi kelompok rentan seperti anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Dr. Satrio menyadari bahwa kaum ibu memegang peranan penting dalam menentukan menu makanan di rumah. Karena itu, ibu menjadi titik sentral dalam perubahan pola makan keluarga.
Operasi Pemberantasan Buta Gizi pun diperkenalkan dengan berbagai kegiatan edukatif, seperti ceramah, kursus memasak, dan pameran makanan yang dilakukan oleh Lembaga Makanan Rakyat (LMR). Program ini tidak hanya menyasar ibu rumah tangga, tetapi juga melibatkan masyarakat secara keseluruhan dalam upaya meningkatkan kesadaran gizi.
Salah satu inovasi penting dalam program ini adalah pengenalan konsep “4 Sehat 5 Sempurna,” yang diciptakan oleh Prof. Dr. Poorwo Soedarmo, seorang ahli gizi terkemuka di Indonesia.
Konsep ini membagi makanan menjadi lima kategori penting: karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Program ini mengajarkan masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang mengandung kelima zat gizi tersebut dalam porsi yang seimbang. Namun, yang menarik dari Operasi Pemberantasan Buta Gizi adalah pendekatannya yang fleksibel sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
Masyarakat diberi kebebasan untuk menyesuaikan konsep 4 Sehat 5 Sempurna dengan potensi sumber daya alam lokal. Misalnya, di daerah pegunungan yang tidak memiliki akses mudah ke ikan, mereka bisa mengganti sumber protein dengan kacang-kacangan atau daging ternak.
Pendekatan ini sejalan dengan semangat Soekarno yang menginginkan masyarakat Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri (Berdikari) dengan memanfaatkan potensi lokal.
Beberapa daerah menunjukkan keberhasilan yang signifikan berkat implementasi revolusi menu ini. Di Gunung Kidul, Yogyakarta, misalnya, di mana tanahnya tandus dan hanya bisa menanam singkong, penduduk mendapatkan bantuan dari ahli gizi untuk mengolah koro benguk, tanaman lokal yang kaya protein.
Meskipun tanaman ini beracun jika tidak diolah dengan benar, para ahli gizi mengajarkan cara mengolahnya dengan aman, sehingga masyarakat bisa mengonsumsi koro benguk sebagai sumber pangan yang bergizi.
Di Wonogiri, Jawa Tengah, meskipun produksi pisang sempat langka, kerja sama antara penduduk dan ahli gizi LMR berhasil mengembalikan produksi pisang yang akhirnya dapat dijual ke daerah lain. Keberhasilan ini menunjukkan bagaimana pendekatan lokal yang tepat dapat menghasilkan perubahan besar dalam pola makan masyarakat, bahkan memengaruhi ekonomi lokal.
Namun, meskipun ada beberapa keberhasilan, tidak semua daerah berhasil menerapkan program ini dengan baik. Menurut disertasi Vivek Neelakantan, beberapa wilayah gagal mencapai tujuan program ini
Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kemerosotan ekonomi, fokus negara yang lebih besar pada konfrontasi dengan Malaysia, serta kekurangan tenaga ahli di daerah-daerah tertentu. Akibatnya, revolusi menu tidak sepenuhnya berhasil di seluruh Indonesia.
Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah kekurangan infrastruktur dan distribusi pangan yang merata. Meski ada kemajuan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi, banyak daerah yang masih kesulitan mengakses bahan pangan bergizi dengan harga terjangkau.
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, program Operasi Pemberantasan Buta Gizi dan revolusi menu yang digagas oleh Sukarno meninggalkan warisan penting bagi sejarah kesehatan masyarakat Indonesia.
Gerakan ini berhasil membuka kesadaran tentang pentingnya pola makan yang seimbang dan keberagaman dalam konsumsi pangan. Meskipun tidak sepenuhnya berhasil di seluruh wilayah, semangat untuk menciptakan kedaulatan pangan dan memperkenalkan pola makan sehat terus bergema hingga hari ini.
Revolusi menu bukan hanya tentang mengganti bahan makanan, tetapi juga tentang mengubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya gizi dan kesehatan. Dengan pendekatan yang tepat dan berkelanjutan, program ini tetap menjadi bagian penting dari perjalanan Indonesia menuju masyarakat yang lebih sehat dan mandiri. (LSA)