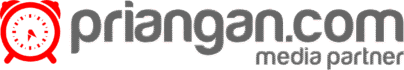CIANJUR | Priangan.com – Beginilah potret terowongan kereta api di Lampegan Cianjur. Terowongan yang satu ini, menjadi salah satu terowongan kereta api tertua di Indonesia. Dibangun pada 1879 dan rampung pada 1882, Lampegan tercatat sebagai bagian penting dalam sejarah jalur kereta api di tanah Priangan.
Gagasan pembangunan jalur ini muncul tidak lama setelah rampungnya rel Batavia–Buitenzorg pada 1878. Pemerintah kolonial Belanda kala itu melihat peluang besar untuk membuka jalur ke Bandung demi memperlancar distribusi hasil bumi, terutama kopi, palawija, dan rempah-rempah. Perusahaan kereta api Staats Spoorwegen kemudian memulai pembangunan dengan cara menggali dari dua sisi, Sukabumi dan Cianjur.
Medan yang sulit menjadi tantangan utama. Kontur pegunungan membuat pengerjaan membutuhkan tenaga manusia dalam jumlah besar. Material kayu serta campuran kapur dan semen digunakan untuk memperkuat sisi terowongan. Sementara itu, di sisi Cianjur, para pekerja harus menghadapi tekanan air yang terus keluar dari tanah sehingga memerlukan pompa bertekanan tinggi untuk mengatasinya.
Pada saat selesai dibangun, panjang Terowongan Lampegan tecatat mencapai 686 meter. Jalur ini resmi digunakan pada 21 Juli 1882 dan menjadi jalur strategis penghubung Batavia, Bogor, Sukabumi, hingga Bandung. Keberadaan Lampegan sekaligus menandai babak baru dalam transportasi kereta api di Jawa Barat, meskipun jalur ini berada di daerah dengan gradien terjal yang cukup ekstrem.
Seiring waktu, terowongan ini pernah mengalami kerusakan serius. Pada 2001, misalnya, sebagian strukturnya ambruk dan membuat layanan kereta api terhenti. Jalur tersebut baru kembali berfungsi pada 2014 setelah dilakukan perbaikan, dan sejak itu KA Siliwangi menjadi rangkaian yang secara reguler melintas melewati Lampegan.
Selain nilai historis, Lampegan juga menyimpan cerita mistis yang berkembang di masyarakat. Salah satu kisah yang kerap diceritakan adalah hilangnya seorang penari ronggeng bernama Nyi Saeda setelah tampil dalam acara peresmian terowongan pada masa kolonial. Hingga kini, cerita itu masih menjadi bagian dari mitos yang melekat pada Lampegan. (wrd)